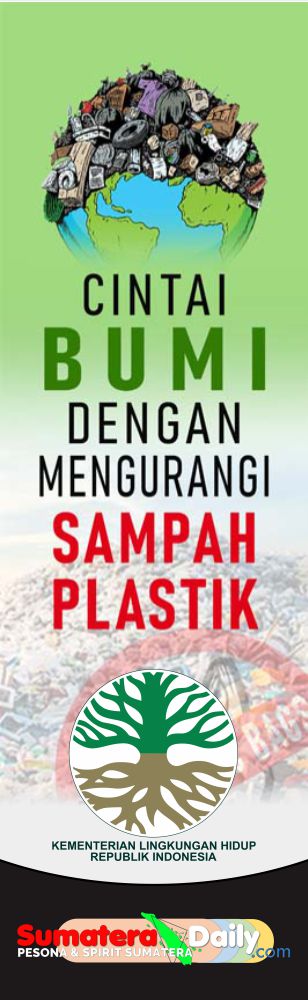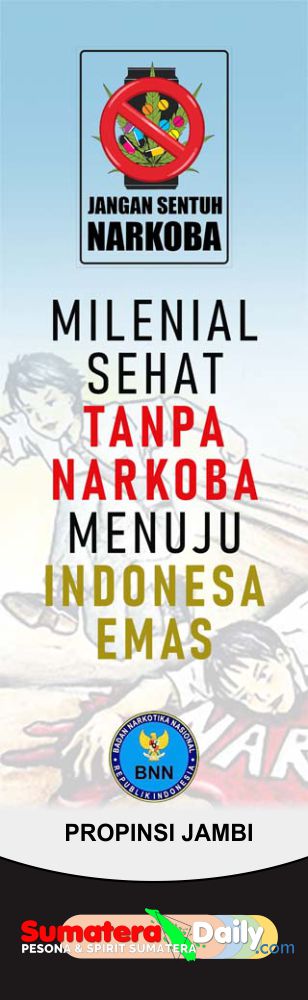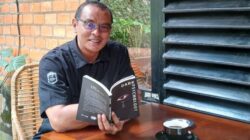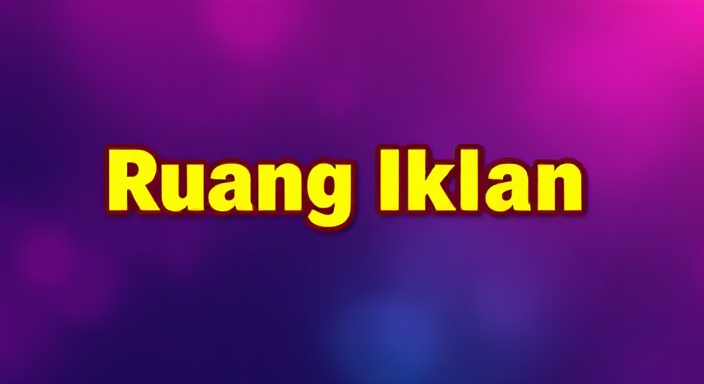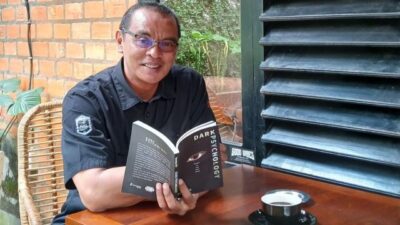Oleh : Mira Natalia Pellu (*)
DALAM perkembangan teknologi digital yang kian pesat, kita dihadapkan pada urgensi untuk meninjau kembali bagaimana relasi antara gender, teknologi dan kekuasaan. Meski ruang digital menawarkan demokratisasi akses dan ekspresi, nyatanya tidak semua pihak dapat menikmati hak yang sama.
Laki-laki dinilai bebas berselancar dan menjamah ruang digital, sementara banyak perempuan justru dibungkam oleh kesenjangan akses dan kekerasan siber. Dalam konteks inilah, pemikir feminis Donna Haraway melalui esainya yang berjudul A Cyborg Manifesto (1985) kembali relevan di bicarakan, karena Ia menyoroti bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menentang batas-batas tradisional antara manusia dan mesin, laki-laki dan perempuan, serta alam dan budaya.
Haraway mendorong feminis untuk meninggalkan pemikiran usang tentang kodrat perempuan yang dianggap tidak selaras dengan teknologi dan justru dapat memanfaatkannya sebagai bagian dari emansipasi.
Sementara itu, istilah cyberfemisme mulai dikenal luas pada tahun 1900-an terinspirasi dari gagasan Haraway, untung menantang pandangan dominan bahwa “teknologi adalah dunia laki-laki” sekalgius mengeksplorasi internet dan media digital sebagai ruang gerak baru bagi gerakan perempuan.
Bagi Haraway langkah transformatif sangat diperlukan untuk melawan bias gender yang selama ini melekat dalam dunia teknologi. Lewat gagasan Cyberfeminisme, Ia menawarkan pendekatan praktis dan teoritis yang bertujuan untuk mendekosntruksi dan merekonstruksi hubungan perempuan dan teknologi. Perempuan tidak hanya didorong untuk akrab dengan teknologi saja melainkan untuk berpikir kritis: siapa yang sebenarnya merancang teknologi yang digunakan setiap hari? Bahasa dan kepentingan siapa yang tersembunyi?
Dari sinilah dapat dilihat bahwa cyberfeminisme tidak hanya berbicara seputar akses melainkan perubahan paradigma. Ia menantang pandangan bahwa teknologi adalah wilayah dari maskulin dan membuka ruang bagi desain teknologi yang lebih inlusif, berperspektif gender, dan memberdayakan sehingga bisa menjadi alat pembebas, bukan penindas. Selain itu melalui konsep “manusia cyborg” yang melampaui identitas biner, maka Haraway mengajak kita membayangkan bagaimana masa depan yang lebih adil dan netral di mana dunia digital dapat melayani semua kalangan.
Teknologi Digital dan Pergerakan Feminisme
Media sosial telah menghadirkan ruang baru bagi mereka yang selama ini bungkam melalui gerakan #MeToo yang menjadi bukti nyata. Dalam riset yang dilakukan oleh Sable Fray (2023), tercatat bahwa pada Oktober 2017, aktris Alyssa Milano memecah keheningan dengan satu cuitan di Twitter. Ia membagikan pengalamannya sebagai penyintas kekerasan seksual sambil mengajak perempuan lain untuk melakukan hal serupa, cukup dengan dua kata: “Me Too.” Respons yang di dapat luar biasa. Dalam waktu singkat, tagar #MeToo tersebar lebih dari 1,7 juta kali di 85 negara. Gelombang solidaritas ini tidak hanya berasal dari masyarakat biasa, tetapi juga dari puluhan selebritas perempuan yang ikut angkat suara. Apa yang awalnya terlihat seperti kampanye media sosial kini berubah menjadi gerakan sosial berskala global.
Cerita-cerita yang selama ini disimpan rapat akhirnya menemukan tempat untuk didengar. Tapi dampaknya tidak berhenti di dunia maya. Gerakan #MeToo mendorong lahirnya perubahan konkret: dari gerakan internal di berbagai industri untuk melawan pelecehan, munculnya inisiatif kebijakan seperti Me Too Congress Act di Amerika Serikat, hingga proses hukum yang akhirnya menjatuhkan vonis pada tokoh-tokoh berkuasa seperti produser Hollywood ternama (Fray, 2023).
Dalam konteks ini, media sosial bukan hanya sekadar ruang berbagi cerita, tetapi sebagai alat pemberdayaan kolektif. Di mana menyatukan para penyintas dan aktivis, mengubah pengalaman pribadi menjadi kekuatan publik, serta menuntut akuntabilitas dari sistem yang selama ini diam. #MeToo mengajarkan kita bahwa di balik setiap unggahan, ada harapan untuk keadilan. Dan kadang, melahirkan perubahan besar dimulai dari suara yang berani berbicara meski hanya lewat satu tagar.
Di Indonesia, semenjak kemunculan teknologi digital telah menjadi alat penting dalam memperluas jangkauan gerakan feminis. Berbagai komunitas dan inisiatif lokal kini semakin aktif memanfaatkan media sosial sebagai wadah advokasi kesetaraan gender. Salah satu contohnya adalah Komunitas Indonesia Feminis yang melalui akun Instagram mereka, @indonesiafeminis, secara konsisten menyuarakan pentingnya pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tidak hanya sekadar kampanye, mereka menggunakan platform ini untuk menyosialisasikan isu-isu penting, mengedukasi publik tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, sekaligus membangun jejaring dengan komunitas lain guna memperkuat barisan perjuangan (Setyaraharjoe dkk., 2023).
Gerakan digital yang di bangun bukan hanya ramai di dunia maya, tetapi juga berdampak nyata. Gelombang dukungan yang terus digelorakan lewat media sosial ikut memberi tekanan politik yang pada akhirnya berhasil mendorong disahkannya UU TPKS pada tahun 2022.
Hal ini menjadi tonggak bersejarah bagi perlindungan korban kekerasan seksual, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Contoh lain datang dari akun Instagram @rahasiagadis yang dikenal dengan konten edukatifnya seputar isu-isu pelecehan seksual. Akun ini tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membuka ruang aman bagi para penyintas untuk berbagi cerita dan saling menguatkan. Penelitian Salim Alatas (2019) menunjukkan bahwa inisiatif ini berhasil membangun komunitas virtual yang aktif dan suportif sehingga memberi ruang partisipasi yang bermakna sekaligus memenuhi kebutuhan psikososial pengikutnya.
Kisah-kisah ini membuktikan bahwa dunia digital telah menghadirkan ruang publik baru bagi perempuan untuk bersuara, terhubung satu sama lain, dan menggalang solidaritas dalam perjuangan menuju kesetaraan yang lebih adil dan inklusif.
Tantangan: Kekerasan Siber dan Kesenjangan Akses
Meskipun era digital membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan memperluas gerakan kesetaraan, namun juga membawa tantangan serius yang tidak dapat diabaikan.
Salah satu bentuk tantangan tersebut adalah meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang mencakup berbagai tindakan seperti perundungan digital, pelecehan seksual di dunia maya, ancaman kekerasan, doxing, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate image sharing atau dikenal pula sebagai revenge porn).
Laporan Komnas Perempuan yang dikutip dalam Jurnal Perempuan (2024) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 1.801 kasus kekerasan seksual berbasis digital. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021 yang mencatat 940 kasus serupa.
Meski demikian, jumlah ini kemungkinan besar belum merepresentasikan keseluruhan kasus yang terjadi. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena merasa tidak aman, malu, atau pesimis terhadap respons aparat penegak hukum dan sistem peradilan yang ada.
Perempuan yang aktif menyuarakan isu-isu kesetaraan gender di media sosial sering kali menjadi sasaran serangan siber, seperti trolling, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan fisik. Serangan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan personal, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental dan menurunkan tingkat partisipasi perempuan dalam diskursus publik digital. Ketika ruang digital yang semestinya menjadi sarana pemberdayaan justru menjadi arena intimidasi, maka demokratisasi partisipasi menjadi terhambat.
Selain itu, media digital juga dinilai memfasilitasi penyebaran cepat terhadap narasi misoginis dan stigma terhadap feminisme. Distorsi informasi serta kampanye misinformasi tentang gerakan feminis kerap kali mempersulit upaya advokasi dan mengaburkan pesan-pesan utama perjuangan kesetaraan gender. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya mendukung emansipasi perempuan sering kali justru menjadi tempat reproduksi kekuasaan patriarkis dalam bentuk baru yang lebih tersembunyi namun sama merusaknya.
Di samping kekerasan berbasis gender di ruang digital, kesenjangan digital berbasis gender masih menjadi persoalan struktural yang signifikan. Baik dalam konteks global maupun nasional, perempuan tercatat memiliki akses yang lebih rendah terhadap teknologi digital dibandingkan laki-laki, terutama di komunitas dengan kondisi ekonomi lemah dan di wilayah-wilayah terpencil. Ketimpangan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur atau perangkat, melainkan juga oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang memperkuat eksklusi digital terhadap perempuan.
Beberapa hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi mencakup keterbatasan finansial, anggapan sosial yang masih mendominasi bahwa teknologi bukanlah ranah perempuan, serta beban ganda domestik yang membatasi waktu dan ruang untuk belajar atau mengembangkan kemampuan digital. Hambatan-hambatan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat literasi digital perempuan, yang pada akhirnya membatasi partisipasi mereka dalam berbagai peluang yang ditawarkan oleh transformasi digital.
Padahal, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sesungguhnya membuka potensi besar bagi pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan. Akses terhadap pendidikan daring, pekerjaan jarak jauh, dan wirausaha digital melalui platform e-commerce merupakan beberapa contoh konkret bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan perempuan.
Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), saat ini 64,5% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah perempuan (KemenPPPA, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses perempuan terhadap pelatihan teknis, literasi digital, permodalan, serta jaringan pasar akan secara langsung berkontribusi terhadap penguatan ekonomi keluarga dan pembangunan nasional secara lebih luas.Dengan demikian, menutup kesenjangan digital gender bukan hanya menjadi agenda keadilan sosial, melainkan juga strategi krusial dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Solusi dan Langkah Kebijakan: Mewujudkan Kesetaraan di Ranah Digital
Melihat kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan dalam ruang digital, negara dinilai perlu mengambil peran proaktif agar teknologi tidak menjadi sumber ketimpangan baru, melainkan wahana pemberdayaan yang inklusif. Penguatan kerangka hukum melalui implementasi regulasi seperti UU TPKS 2022, UU ITE 2008, dan UU PDP 2022 harus dilakukan dengan pendekatan berperspektif korban dan disesuaikan dengan dinamika kekerasan digital yang terus berkembang (Aripkah et al., 2024; Jurnal Perempuan, 2024)
Penegak hukum perlu dibekali pelatihan yang menanamkan sensitivitas gender agar mampu menafsirkan aturan secara adil dan berpihak pada korban, bukan malah melanggengkan ketidakadilan. Revisi terhadap pasal-pasal bermakna ganda, khususnya dalam UU ITE, juga menjadi krusial agar korban merasa aman untuk melapor tanpa risiko dikriminalisasi. Keseluruhan kebijakan yang dihadirkan negara wajib responsif terhadap kesetaraan gender dalam konteks digital, sebab jika hukum tertinggal dari laju perkembangan kekerasan daring, maka perlindungan yang dijanjikan akan kehilangan makna substantif.
Kedua, menutup kesenjangan akses terhadap teknologi digital sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan kesetaraan gender di era digital. Program literasi digital berbasis gender, dukungan infrastruktur, serta akses terhadap permodalan dan perangkat digital perlu dirancang secara inklusif, terutama bagi perempuan di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Dalam studi yang dilakukan oleh Alatas (2019) menunjukkan bahwa inisiatif digital yang berpihak pada perempuan mampu membangun partisipasi bermakna dan memperkuat kapasitas komunitas virtual perempuan.
Ketiga, menciptakan ruang digital yang aman juga mendesak dilakukan. Platform media sosial harus dilibatkan dalam memastikan sistem pelaporan kekerasan yang responsif, serta penerapan moderasi konten misoginis dan sanksi bagi pelaku. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan regulasi, seperti yang diatur dalam UU TPKS dan UU PDP, agar benar-benar melindungi perempuan dari kekerasan siber yang kian kompleks (Setyaraharjoe et al., 2023)
Keempat, mendukung partisipasi perempuan dalam ekosistem teknologi merupakan langkah penting untuk memastikan transformasi digital yang adil dan setara. Prinsip-prinsip cyberfeminisme mendorong keterlibatan perempuan tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai perancang, inovator, dan pengambil keputusan dalam ruang digital. Peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang STEM serta posisi strategis di industri digital perlu difasilitasi melalui kebijakan afirmatif yang terstruktur. Setyaraharjoe et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam komunitas digital memperkuat kapasitas advokatif dan membuka ruang partisipasi bermakna di tengah dominasi budaya digital yang masih maskulin. Untuk itu, baik pemerintah maupun sektor swasta harus berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung pengembangan karier perempuan, serta menghasilkan produk teknologi yang bebas dari bias gender.
Pada akhirnya, visi cyberfeminisme yang digagas Donna Haraway menjadikan teknologi sebagai mitra dalam perjuangan menuju masyarakat yang adil gender hanya dapat direalisasikan melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi. Pemerintah, sektor swasta, komunitas, institusi pendidikan, media, dan masyarakat sipil perlu bersinergi dalam membongkar bias gender yang telah lama melekat dalam ekosistem digital.
Meski hal ini menantang tatanan sosial dan struktur kekuasaan yang mapan, reformasi kebijakan yang inklusif dan partisipatif menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang setara dan aman bagi semua. Dalam kerangka ini, teknologi tidak lagi diposisikan sebagai instrumen yang mereproduksi ketimpangan, melainkan sebagai medium transformasi sosial yang mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan gender secara substantif di era digital. ***
(*) Penulis Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta, artikel ini dilansir dari laman media partner sumateradaily.com (indonesiadaily.go.id – Asri Media group)