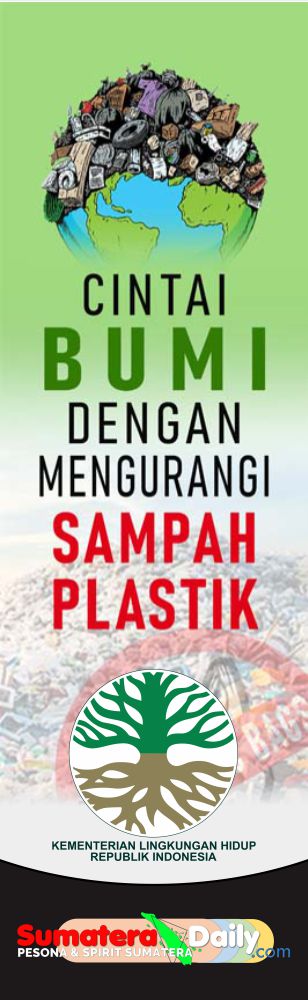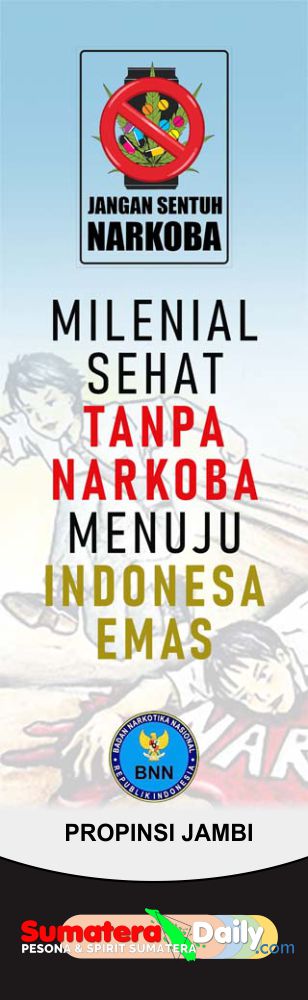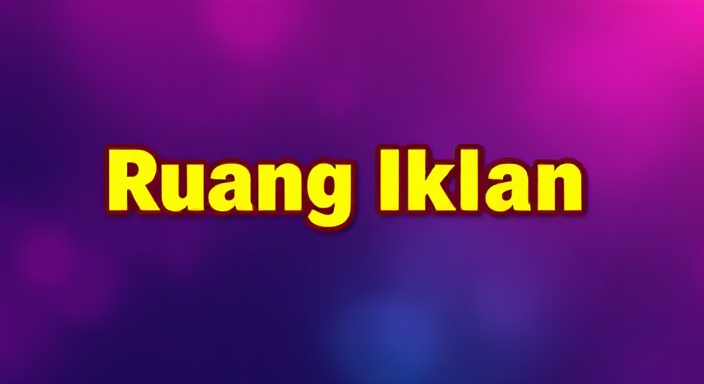Oleh: Martayadi Tajuddin
Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di Kota Jambi menyuguhkan sebuah peristiwa kompleks yang tidak bisa dipandang sekadar urusan infrastruktur semata.
Proyek ini menjadi titik temu antara ambisi investasi ekonomi dan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
Di sinilah masalah mendasar muncul: Apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar memperhatikan kaidah hukum dan prinsip keadilan ekologis? Atau justru menjadi contoh kegagalan tata kelola lingkungan dan ruang di Indonesia?
Konstruksi di Atas Lahan Rawan Konflik
Secara teknis, PT SAS mengklaim telah menjalankan prosedur perizinan dan AMDAL sesuai ketentuan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: proyek ini beroperasi di kawasan yang seharusnya dilarang untuk kegiatan industri berat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi, yang menetapkan lokasi tersebut sepertinya sebagai zona permukiman dan ruang terbuka hijau.
Alih-alih mengedepankan prinsip kehati-hatian, proyek ini justru memaksakan konstruksi di atas lahan rawa yang sensitif terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan risiko banjir dan pencemaran.
Konstruksi ini tidak hanya merusak ekosistem lokal, tapi juga mengancam keberlangsungan pasokan air bersih bagi ribuan warga yang bergantung pada sumber air di sekitar lokasi.
Intake PDAM Kota Jambi yang dekat dg lokasi TUKS akan memberikan potensi pencemaran air baku bukanlah isu sepele, melainkan alarm yang harusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan pelaku usaha.
Kontroversi: Suara Warga di Pinggirkan
Kontroversi yang mencuat bukan hanya soal teknis atau regulasi, melainkan juga soal hak warga untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2009 secara jelas menegaskan bahwa penyusunan AMDAL harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat terdampak.
Namun, warga Aur Kenali dan Mendalo Laut menyatakan bahwa suara mereka diabaikan dan sosialisasi yang dilakukan bersifat formalitas semata.
Di sinilah problem besar tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan seringkali gagal: ketika kepentingan investasi diletakkan lebih tinggi dibandingkan hak dasar warga dan keberlanjutan ekosistem.
Jika pembangunan ini dibiarkan berjalan tanpa evaluasi ulang yang kritis, maka yang terjadi adalah legitimasi pembangunan yang rapuh, yang pada akhirnya dapat berujung pada kerusakan sosial-ekologis yang sulit diperbaiki.
Komitmen Lingkungan: Retorika atau Realita?
Indonesia memiliki regulasi yang jelas dan ketat terkait perlindungan lingkungan dan penataan ruang.
Namun, implementasi di lapangan seringkali jauh dari harapan. Kasus PT SAS menjadi contoh nyata betapa komitmen terhadap lingkungan masih sebatas retorika.
Jika benar PT SAS memiliki AMDAL yang valid dan izin lengkap, kenapa sampai muncul penolakan masif dari masyarakat dan kekhawatiran pencemaran air baku PDAM? Jika regulasi ditaati dengan cermat, mengapa masih ada penolakan proyek ini? Jawabannya sederhana: ada ketidaksesuaian antara dokumen administratif dan realitas dampak lingkungan dan sosial.
*Sebuah Panggilan untuk Refleksi dan Tindakan Nyata*
Kasus TUKS PT SAS bukan sekadar persoalan lokal, melainkan cermin dari tantangan besar pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Investasi tidak boleh menjadi legitimasi bagi perusakan lingkungan dan pengabaian hak warga.
Sebaliknya, harus ada sinergi yang nyata antara pembangunan fisik, perlindungan sosial, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Pemerintah, sebagai regulator dan pelindung kepentingan publik, harus berani meninjau ulang perizinan ini secara transparan dan objektif.
Warga harus diberikan ruang untuk berpartisipasi penuh, bukan sekadar prosedural. Investor harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
Jika tidak, pembangunan yang semestinya menjadi simbol kemajuan justru akan menjadi sumber konflik, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan sosial. (*)
* Tenaga Pengajar pada Prodi Arsitektur Universitas Adiwangsa Jambi