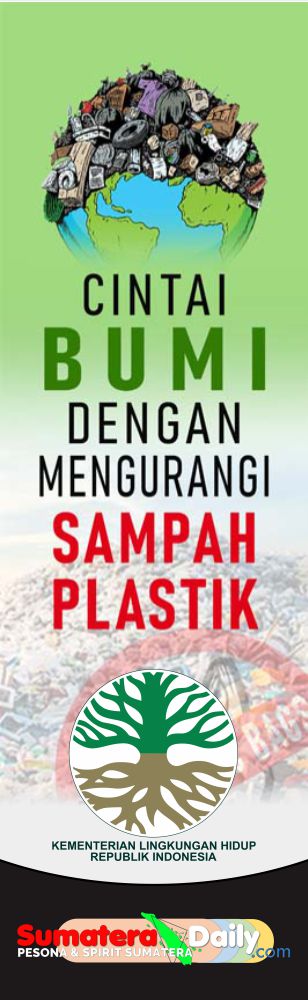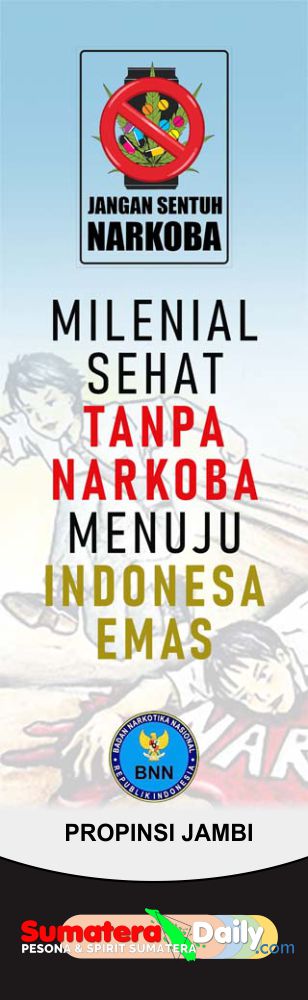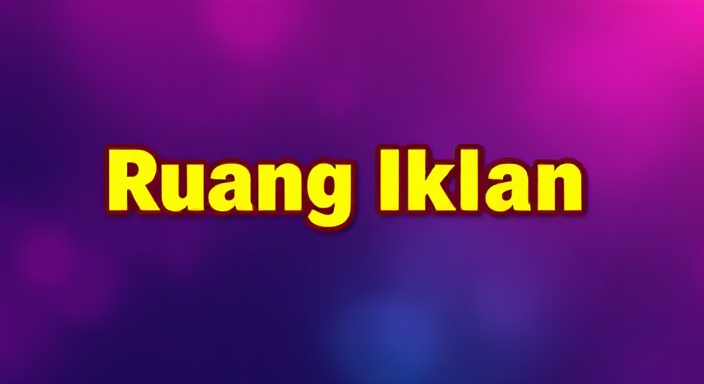Oleh: Wahyu Adi Setyo Wibowo (*)
BAYANGKAN jika seluruh keputusan penting pemerintah tidak didokumentasikan. Tidak ada salinan surat, tidak ada notulensi rapat, dan tidak ada catatan anggaran. Apa yang terjadi? Kekacauan.
Dalam dunia birokrasi, arsip adalah ingatan organisasi. Tanpanya, kebijakan tidak bisa ditelusuri, tanggung jawab tak bisa dimintai, dan publik tidak bisa percaya.
Di sisi lain, kita hidup di era keterbukaan dan komunikasi digital. Semua peristiwa bisa menjadi konsumsi publik dalam hitungan detik.
ASN (Aparatur Sipil Negara) dan instansi pemerintah kini tak hanya dituntut bekerja baik, tetapi juga mampu menjelaskan dan membuktikan kerja tersebut. Di sinilah arsip dan komunikasi saling bersentuhan.
Sering kita menganggap arsip sebagai tumpukan kertas, atau folder digital yang hanya dibuka saat audit.
Padahal, dari sudut pandang teori komunikasi, arsip adalah pesan yang dikirimkan ke masa depan. Ia adalah bukti, narasi, dan instrumen legitimasi.
Teori komunikasi klasik dari Shannon dan Weaver menyebut bahwa komunikasi adalah proses mengirim pesan dari pengirim ke penerima.
Nah, dalam birokrasi, ASN adalah pengirim, arsip adalah medianya, dan publik—termasuk generasi mendatang—adalah penerimanya.
Jika arsip rusak, hilang, atau tidak dapat diakses, maka komunikasi itu gagal. Akibatnya? Publik kehilangan kepercayaan, dan birokrasi kehilangan legitimasi.
Dalam memahami peran arsip di lingkungan pemerintahan, kita dapat meminjam perspektif dari berbagai teori komunikasi.
Teori-teori ini menawarkan cara pandang yang kaya dalam menilai betapa strategisnya posisi arsip, tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, pengaruh, dan pembentuk makna dalam kehidupan sosial.
Berikut ini adalah penjabaran beberapa teori komunikasi yang relevan untuk menelaah pentingnya arsip dalam mendukung kinerja dan legitimasi institusi publik, khususnya birokrasi.
1. Agenda-Setting Theory: Menentukan Apa yang Dianggap Penting
Teori Agenda-Setting yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972 menyatakan bahwa media tidak secara langsung mempengaruhi apa yang orang pikirkan, tetapi sangat berhasil dalam memengaruhi apa yang orang anggap penting. Dengan kata lain, media memiliki kekuatan dalam menetapkan agenda isu publik.
Dalam konteks ini, arsip menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sumber data dan informasi yang dapat mengimbangi dominasi narasi yang dibentuk media.
Ketika isu-isu tertentu menjadi perbincangan publik akibat pemberitaan yang intens, pemerintah dituntut untuk memberikan tanggapan yang terukur dan berbasis fakta.
Tanpa dokumentasi yang baik, pemerintah kehilangan dasar untuk membentuk narasi tandingan atau memberikan klarifikasi.
Arsip yang tersimpan secara sistematis menjadi bukti konkret yang dapat digunakan untuk memperjelas konteks, meluruskan kesalahpahaman, dan menunjukkan proses pengambilan keputusan yang sah.
Dengan demikian, arsip memperkuat posisi lembaga pemerintah dalam menetapkan ulang agenda komunikasi publik.
Sebagai contoh, dalam isu pengelolaan anggaran atau kebijakan publik yang mendapat sorotan media, instansi pemerintah dapat mengandalkan arsip notulensi rapat, surat keputusan, atau dokumen evaluasi untuk memperlihatkan proses akuntabilitas yang sudah dijalankan.
Tanpa arsip, narasi pemerintah bisa menjadi lemah atau bahkan terkesan defensif.
2. Symbolic Interactionism:
Arsip sebagai Simbol Sosial
Symbolic Interactionism adalah teori komunikasi yang menekankan bahwa manusia berinteraksi berdasarkan makna yang mereka lekatkan pada simbol, dan makna tersebut dibentuk melalui proses sosial. Herbert Blumer, yang mengembangkan teori ini dari pemikiran George Herbert Mead, menyatakan bahwa tindakan manusia tidak didorong oleh realitas objektif, tetapi oleh interpretasi terhadap simbol.
Dalam birokrasi, arsip tidak hanya dipahami sebagai kumpulan dokumen, tetapi juga sebagai simbol dari proses, keputusan, dan otoritas. Misalnya, sebuah surat keputusan tidak hanya berisi perintah administratif, melainkan juga merepresentasikan legitimasi pejabat yang mengeluarkannya serta proses hukum atau tata kelola yang menyertainya.
Maka, keberadaan dan pengelolaan arsip turut memperkuat nilai simbolik dari suatu tindakan birokrasi.
Tanpa pengelolaan arsip yang baik, simbol-simbol ini kehilangan konteks. Surat perintah bisa dianggap tidak sah jika tidak ditemukan dokumen pendukungnya.
Lebih dari itu, ketiadaan arsip dapat menimbulkan kekosongan makna, sehingga membuka ruang bagi spekulasi atau distorsi dalam interpretasi publik.
Oleh karena itu, arsip perlu dipahami sebagai bagian dari sistem makna sosial yang menjaga konsistensi simbol dalam komunikasi kelembagaan.
3. Spiral of Silence: Arsip sebagai Dasar untuk Berpendapat
Teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann pada tahun 1974 menjelaskan mengapa individu atau kelompok sering kali memilih untuk diam dalam konteks sosial.
Teori ini menyatakan bahwa seseorang cenderung bungkam jika merasa pendapatnya berbeda dari mayoritas, karena takut dikucilkan atau tidak diterima secara sosial.
Dalam dunia birokrasi dan tata kelola publik, kondisi ini sangat mungkin terjadi, apalagi ketika sebuah isu menjadi kontroversial.
Namun, keberadaan arsip yang lengkap dan autentik dapat menjadi penopang bagi seseorang atau institusi untuk tetap bersuara.
Ketika opini mayoritas tidak sepenuhnya didasarkan pada data, arsip berfungsi sebagai pijakan argumentatif yang sah.
Bagi ASN, keberadaan arsip bukan hanya alat administrasi, tetapi juga sarana untuk membuktikan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil didasarkan pada prosedur dan dokumen yang valid.
Dengan kata lain, arsip memberi keberanian kepada individu untuk tampil dan menyuarakan fakta, bahkan di tengah tekanan opini publik.
Di lingkungan pemerintahan, ini sangat penting untuk menjaga kejujuran, menghindari scapegoating, dan membangun narasi berbasis data.
Dalam situasi tertentu, arsip bahkan bisa menjadi alat perlindungan terhadap tindakan yang tidak berdasar atau tuduhan sepihak.
4. Foucault dan Kekuasaan
Melalui Arsip: Menentukan Apa yang Diingat dan Dilupakan
Michel Foucault, seorang filsuf dan pemikir strukturalis asal Prancis, memiliki pandangan yang tajam mengenai arsip.
Dalam bukunya The Archaeology of Knowledge (1969), Foucault menyatakan bahwa arsip bukan hanya kumpulan dokumen, melainkan sistem yang menentukan apa yang boleh dikatakan, siapa yang boleh berkata, dan bagaimana sesuatu bisa menjadi “pengetahuan yang sah”.
Dalam konteks kekuasaan, Foucault melihat arsip sebagai alat yang digunakan oleh otoritas untuk mengontrol narasi sejarah dan mengarahkan ingatan kolektif masyarakat. Yang terdokumentasi akan terus diingat dan dijadikan referensi resmi.
Sebaliknya, yang tidak pernah dicatat atau diarsipkan akan terlupakan seolah-olah tidak pernah terjadi.
Implikasi dari pandangan ini sangat besar.
Jika suatu peristiwa penting dalam pemerintahan tidak terdokumentasikan secara formal, maka ia tidak memiliki eksistensi dalam sejarah kelembagaan.
Maka, pengelolaan arsip bukan hanya soal administratif, tapi juga soal kuasa—kuasa untuk menentukan apa yang diingat, dan apa yang dihapus dari narasi resmi.
Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa tanggung jawab arsiparis, pejabat pengelola arsip, dan ASN secara umum bukan hanya mencatat, tetapi juga menentukan sejarah yang akan dikenang oleh publik dan institusi.
ASN bukan sekadar pelaksana aturan.
Dalam era digital, ASN adalah komunikator kebijakan. Ia harus mampu menjelaskan kinerja, mempertanggungjawabkan keputusan, dan berkomunikasi dengan publik.
Namun semua itu butuh dasar: arsip yang rapi dan dapat diakses. Ketika publik bertanya “Mengapa kebijakan ini diambil?”, arsip bisa menjawab.
Ketika media menyorot dugaan ketidaktertiban, dokumen yang sah bisa menjadi pelindung.
Saat ini pemerintah telah mengembangkan sistem seperti SRIKANDI dan NADINE untuk digitalisasi arsip. Ini langkah maju.
Tapi digitalisasi bukan sekadar memindai dokumen—melainkan membangun sistem komunikasi baru yang:
Real-time,
Terhubung antarinstansi,
Bisa diakses publik secara bijak.
ASN perlu dilatih bukan hanya untuk membuat dokumen, tapi juga mengelolanya sebagai bagian dari narasi institusional.
Publik sering mendengar jargon: “transparansi”, “akuntabilitas”, “reformasi birokrasi.” Tapi bagaimana membuktikannya? Jawabannya: arsip.
Transparansi = bisa menunjukkan proses.
Akuntabilitas = bisa mempertanggungjawabkan.
Reformasi = bisa melacak perubahannya.
Dan semua itu hanya mungkin jika arsip terkelola baik dan menjadi bagian dari sistem komunikasi yang hidup.
Tujuh Langkah Memperkuat Sinergi Arsip dan Komunikasi
Jadikan arsip bagian dari strategi komunikasi publik.
Bukan hanya menyimpan, tapi menyampaikan.
Libatkan arsiparis dalam penyusunan narasi lembaga.
Mereka tahu sejarah, tahu konteks.
Latih ASN dalam literasi dokumentasi dan media.
Supaya tahu kapan harus bicara, dan data apa yang harus dibawa.
Bangun budaya dokumentasi.
Setiap keputusan penting harus tercatat sejak awal.
Gunakan arsip sebagai dasar klarifikasi publik.
Termasuk saat terjadi krisis komunikasi.
Kolaborasikan Humas dan Unit Kearsipan.
Narasi tanpa bukti = lemah. Bukti tanpa narasi = sunyi.
Dorong publikasi arsip sebagai edukasi. Misalnya, melalui portal informasi publik berbasis arsip.
Bangsa yang besar bukan hanya yang membuat kebijakan baik, tetapi juga yang mampu mengingat, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan itu.
Di sinilah arsip menjadi penopang komunikasi birokrasi yang sehat.
Jika ASN adalah wajah negara, maka arsip adalah memori dan suara negara.
Keduanya harus bekerja bersama untuk menciptakan birokrasi yang terbuka, cerdas, dan dipercaya. Saatnya kita berhenti memisahkan antara urusan dokumen dan komunikasi.
Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama: kepercayaan publik.
(*) Penulis adalah Arsiparis Ahli Muda Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Doktor Ilmu Komunikasi (Candidate), Universitas Sahid Jakarta