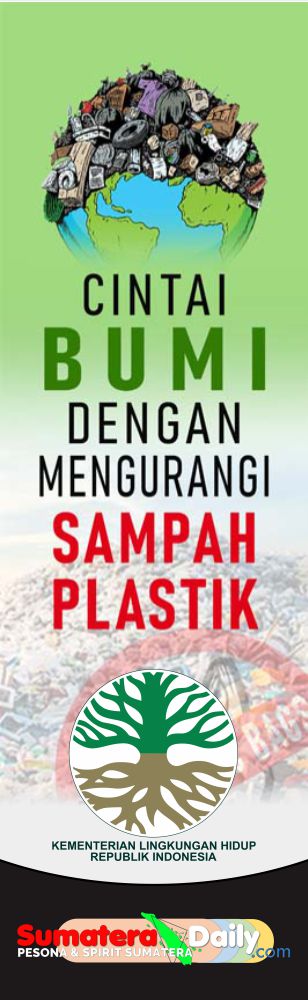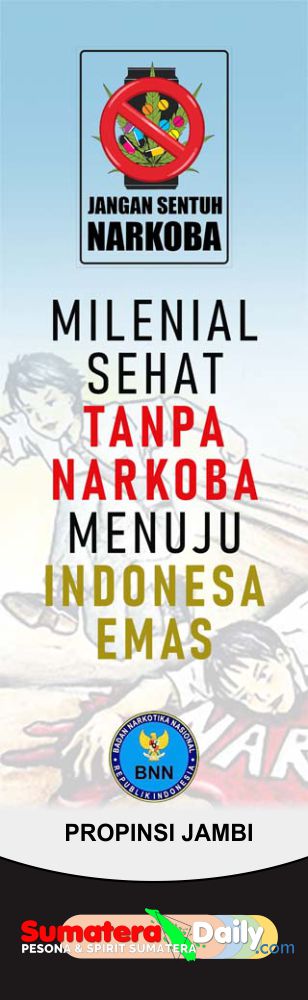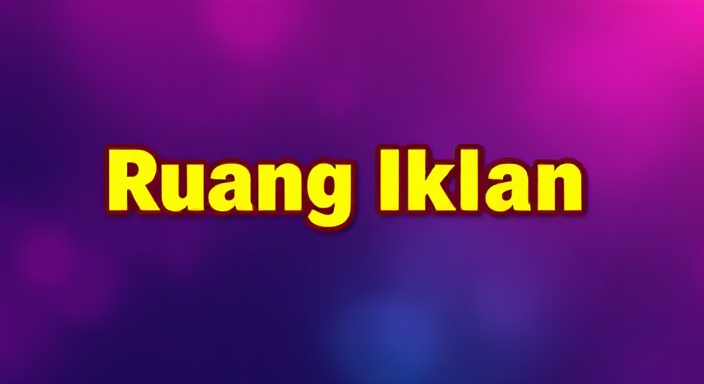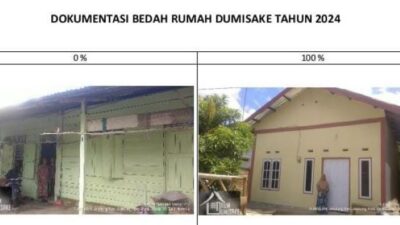Oleh: Dr. Noviardi Ferzi*
DI TENGAH hiruk pikuk pembangunan dan narasi ketahanan pangan nasional, sebuah ancaman senyap tengah merayap di Aur Kenali, Jambi.
Bukan dengan kekuatan militer, melainkan melalui dugaan penyalahgunaan izin dan manipulasi tata ruang, masyarakat lokal menghadapi pengusiran senyap (silent eviction) dari tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun.
Praktik semacam ini, yang diduga dilakukan oleh PT. SAS dengan menumpuk batubara di zona pertanian, bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sebuah penggerusan fundamental terhadap hak-hak masyarakat dan potensi pangan Jambi di masa depan.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 secara gamblang telah menetapkan Aur Kenali sebagai zona krusial untuk permukiman, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan yang terpenting, pertanian.
Penumpukan batubara, sebuah aktivitas yang secara inheren bersifat ekstraktif dan merusak lingkungan, adalah antitesis dari peruntukan tersebut.
Keberadaan fasilitas PT. SAS, yang mencakup jalan khusus, stockpile, dan Terminal Umum untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di zona pertanian, secara terang-terangan melanggar prinsip keselarasan pembangunan dengan RTRW, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Ironisnya, di saat Presiden Prabowo menggaungkan program ketahanan pangan sebagai prioritas nasional, Jambi justru dihadapkan pada praktik yang mengancam fondasi ketahanan pangan lokal.
Pengalihfungsian lahan pertanian produktif secara ilegal akan mengakibatkan erosi lahan pertanian abadi, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Seperti yang ditegaskan Wiradi (2000) dalam analisisnya tentang tanah dan petani, perlindungan lahan pertanian adalah kunci keberlanjutan hidup masyarakat. Jika preseden ini dibiarkan, bukan hanya Jambi yang akan kehilangan potensi pangannya, tetapi juga akan mengirim sinyal buruk bagi komitmen nasional terhadap ketahanan pangan.
Fenomena silent eviction terjadi ketika masyarakat secara bertahap dipaksa meninggalkan tanah mereka bukan melalui penggusuran paksa secara langsung, melainkan melalui mekanisme tidak langsung seperti pencemaran lingkungan, hilangnya akses, atau perubahan peruntukan lahan yang tidak adil.
Di Aur Kenali, aktivitas penumpukan batubara PT. SAS, jika terbukti menyalahi aturan, adalah contoh nyata dari silent eviction.
Dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat masif dan melumpuhkan. Penumpukan batubara tanpa pengelolaan yang memadai akan menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, sebagaimana diuraikan oleh Kusmana (2010) dalam studinya tentang hidrologi pertambangan.
Debu batubara yang bertebaran akan mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat dan mencemari lahan pertanian, menurunkan produktivitas tanaman. Lebih lanjut, keberadaan stockpile batubara skala besar jelas memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang sesuai, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Jika izin pertanian digunakan sebagai kamuflase, ini mengindikasikan ketiadaan dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan batubara, berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Di sisi sosial, silent eviction ini akan melahirkan kemiskinan struktural bagi petani yang kehilangan mata pencarian. Mereka akan terpaksa beralih profesi atau menjadi buruh serabutan, terlepas dari ikatan sosial dan ekonomi yang telah lama terbangun di lingkungan pertanian.
Scott (1998) dalam karyanya Seeing Like a State, mengingatkan bahwa skema pembangunan yang terpusat seringkali gagal ketika tidak sesuai dengan realitas lokal dan kebutuhan sesungguhnya. Dalam kasus Aur Kenali, skema logistik batubara yang bersembunyi di balik izin pertanian berpotensi mengabaikan realitas dan kebutuhan fundamental masyarakat petani.
Klaim PT. SAS yang menyatakan fasilitas infrastruktur logistiknya diperuntukkan bagi sektor pertanian perlu dipertanyakan secara serius. Skala kebutuhan logistik yang sedemikian masif untuk komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, atau kopi di Jambi, sehingga harus mengorbankan lahan pertanian, adalah sebuah anomali. Satu-satunya cara untuk membuktikan klaim ini adalah dengan membuka seluruh dokumen perizinan kepada publik secara transparan.
Masyarakat memiliki hak penuh untuk mengakses dan meninjau setiap izin yang menjadi dasar operasional PT. SAS, termasuk Izin Usaha Perdagangan (IUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Izin Lingkungan.
Penting untuk memastikan apakah dokumen-dokumen tersebut secara eksplisit hanya mencantumkan komoditas pertanian dan perkebunan, ataukah terdapat klausul ambigu, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang umum, atau interpretasi ganda yang memungkinkan masuknya komoditas pertambangan seperti batubara di kemudian hari.
Transparansi perizinan adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan publik; tanpanya, janji “bukan batubara” akan menjadi janji hampa yang berpotensi menciptakan preseden buruk bagi pembangunan di Jambi, bahkan dapat mengindikasikan upaya penghindaran pajak, sebagaimana disoroti oleh Ross (2012) terkait kompleksitas fiskal dari komoditas ekstraktif.
Dugaan penyalahgunaan izin pertanian untuk penumpukan batubara oleh PT. SAS adalah pelanggaran serius terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah, masyarakat, dan pihak berwenang harus bertindak tegas untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan di Jambi. Seperti yang diutarakan Tjokroamidjojo (2000), ini merupakan ujian nyata terhadap komitmen pemerintah dalam menata ruang dan menjamin kesejahteraan publik.
Pembangunan infrastruktur logistik adalah investasi jangka panjang yang akan membentuk wajah dan arah pembangunan Jambi di masa depan. Jika komitmen untuk mendukung sektor pertanian secara berkelanjutan adalah tujuan utama, maka seluruh aspek perizinan, tata ruang, hingga operasional fasilitas logistik harus selaras dan berorientasi pada semangat tersebut. Jangan sampai, di balik “dukungan” terhadap pertanian, justru tanpa disadari membuka celah bagi dominasi komoditas lain yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru dan memperparah persoalan yang sudah ada, serta berujung pada pengusiran senyap masyarakat dari tanahnya sendiri.
Masyarakat Jambi sudah sangat cerdas dan mampu membedakan antara janji manis dan realitas pahit. Mari bersama-sama mengawal pembangunan ini agar benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Jambi, bukan hanya segelintir pihak, dan yang terpenting, sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati bersama.
(*)Penulis Seorang Pemerhati Sosial Ekonomi Lingkungan
Daftar Pustaka
Kusmana, C. (2010). Hidrologi Pertambangan. IPB Press.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ross, M.L. (2012). The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton University Press.
Scott, J.C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press.
Tjokroamidjojo, B. (2000). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Lembaga Administrasi Negara.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Wiradi, G. (2000). Tanah dan Petani: Agenda Masalah dan Kebijakan. Karsa.
Edit