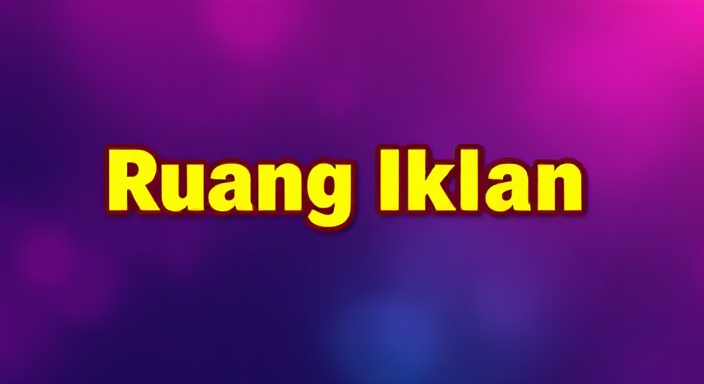Catatan Hendro Basuki
MENJADAI ahli fisika berbeda jalan menjadi ahli politik. Untuk menjadi ahi fisika tak perlu membaca Physics-nya Aristoteles, atau harus membaca karya Newton, dan Galileo. Tiba-tiba saja, oleh sebuah peristiwa alam yang tak dirancang, seseorang bisa memahami bekerjanya fisika.
Berbeda untuk menjadi ahli politik, kita mesti membaca banyak sekali buku seperti Plato, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Marx, Mill, dan sangat perlu membaca Machiavelli.
Tetapi membaca teks atau buku tanpa interpretasi sangat berbahaya. Sama bahayanya jika salah dalam menginterpretasi. Bahkan bisa menimbulkan kerusakan, korban dalam jumlah besar.
Kesalahan menginterpretasi teks kitab suci telah melahirkan ekstremis dan konflik tak berkesudahan.
Oleh sebab itu, menginterpretasi teks membutuhkan cara, pedoman, metodologi agar teks dipahami secara utuh, baik, dan benar. Meski pun, interpretasi itu sendiri bisa saja dikritisi.
Cara orang menginterpretasi makna teks berdampak pada perbuatan kemudian terkait interpretasi yang dilakukan atas teks.
Interpretasi Pol Pot atas ajaran Lenin dan Stalin menghadirkan horor kemanusiaan. Demikian juga interpretasi Ketua Mao atas teks Marxisme. Atau Hitler menginterpretasi teks dari Nietzsche.
Oleh sebab itu, setiap kali seseorang mengkaji sesuatu harus memperlakukan teks bukan sebagai kitab suci. Kenapa? Teks tersebut tetaplah teks yang dihasilkan dari gagasan manusia. Bukan wahyu Tuhan.
Mengungkap Makna
Membaca teks tujuannya adalah mengurangi atau meminimalkan rasa asing dari teks atau menjadikannya lebih familiar dan mudah dimengerti oleh khalayak. Teks yang dihasilkan oleh kebudayaan politik sebelum kita mesti dibaca dengan hati-hati. Meskipun telah dibaca dengan hati-hati dan cermat, kadang teks tak mampu mengungkapkan seluruh makna sesungguhnya.
Para ahli yang meneliti kebudayaan Mesir kuno sering kali menemui jalan buntu dalam menerjemahkan sesuatu artefak. Demikian juga para peneliti kebudayaan Babilonia, kesulitan memahami makna suatu teks Arkadia.
Sampai hari ini para ahli masih menafsir apa makna ” dusta mulia ” ketika Plato menganjurkan penggunaan kata itu. Juga, apa maksud Machiavelli saat membandingkan nasib baik (fortuna) seperti wanita yang harus dipukul.
Menafsir Manusia
Teks yang bertebaran dalam buku kuno saja masih sering sulit diinterpretasi, apalagi memahami manusia politik.
Di antara kita banyak yang bertanya, kenapa Ir Soekarno di satu sisi mempercayai Tuhan yang Maha Esa, tetapi di sisi lain menolak membubarkan PKI. Kenapa pula Dipa Nusantara Aidit yang relegius menjadi Ketua Umum PKI? Kenapa Soeharto yang murah senyum menjadi tegas dan keras di sisi yang lain?
Membaca manusia politik Indonesia tidak bisa sekadar membaca teks. Menginterpretasi Soekarno bisa dengan membaca seluruh karyanya. Tetapi membaca manusia Soekarno membutuhkan interpretasi agar mendekati kesahihan?.
Kenapa Soekarno merasa perlu beristri lebih dari satu? Ini tentu tak bisa dengan membaca teks dari karya pribadi atau karya orang lain. Mungkin saja, beliau melakukan itu karena terilhami untuk “menaklukkan” atau lebih halus membangun “persaudaraan” dengan perikatan perkawinan dengan suku Jawa, Sunda, Minang, Sulawesi, dan lain-lain.
Betapa bangganya perempuan saat itu disunting Bung Karno. Dan, perlu juga dipahami, Soekarno itu wilayah kekuasaannya setara Prabu Brawijaya (Hayam Wuruk) zaman Majapahit.
Kebudayaan yang membentuk Soekarno masih sangat kental dengan feodalisme, di mana raja merupakan gung binatara . Menguasai semesta alam.
Demikian juga memahami Soeharto dengan seluruh tindakannya sebagai manusia politik. Dibesarkan dalam tradisi Jawa pedesaan, dan prajurit maka seluruh strategi politik yang dibangun sebagai manusia Jawa yang berpolitik, tak akan jauh dari tradisi tata tentrem kerta tur raharja . Bahwa dibutuhkan ketentraman untuk mewujudkan kemakmuran.
Lalu bagaimana dengan Presiden Joko Widodo? Cara kita menafsirkan performa Jokowi tidak bisa berbekal pada referensi atau teks-teks politik biasa itu. Kita mesti membaca sejarah, dan kultur Solo yang membentuknya. Seperti Pak Harto, Jokowi juga menampilkan citra yang sederhana. Wajah ndesa nya sangat kental, cara berjalannya seperti orang Solo umumnya. Kosa katanya terbatas, dan tak pula meledak-ledak.
Tetapi jika tak suka, seperti dikatakan Panda Nababan, Tjahyo Kumolo hanya berkomunikasi dua kali saja selama menjadi Mendagri.
Keluar dari Bayangan
Penulis mencoba membaca Jokowi dengan seluruh tindakan politiknya akhir-akhir ini dari perspektif budaya Jawa.
Ada peribahasa Jawa berbunyi “sak dumuk bathuk sak nyari bumi” . Arti bebasnya, satu kali tudingan bisa seluas jagat. Satu kali ejekan, maka kehormatan harus dipertaruhkan. Bahkan harus diperjuangkan sampai mati.
Pangeran Diponegoro melakukan perang ketika makam leluhurnya dilanggar. Pangeran Sambernyawa memberontak karena kehormatannya disisihkan. Sak dumuk bathuk sak nyari bumi.
Lalu Jokowi? Beliau de facto dan de jure adalah Presiden Republik Indonesia. Negara seluas separo Benua Eropa.
Tetapi betapa seperti tidak berharganya kedudukan Jokowi selalu diulang-ulang sebagai petugas partai oleh Megawati Soekarnoputri. Benar secara de facto. Tetapi, kata orang Jawa, benar saja tidak cukup. Harus komplet. Bener lan pener . Benar, dan tepat. Benar faktanya, tetapi tepat posisi dan cara menerapkan atau mengungkapkannya.
Dampak dari ucapan Bu Mega luar biasa. Bukan untuk memahamkan, malah semakin liar yang mengesankan bahwa presiden adalah sekadar petugas. Setinggi-tingginya apa jika dikatakan sebagai petugas. Padahal ada kata yang artinya sama, tetapi bermakna lebih tinggi. Duta Partai misalnya.
Lalu, episode berikutnya, ketika di depan seluruh kader dan disiarkan secara terbuka Bu Mega mengulangi lagi dengan tone tinggi. Bahkan lebih dari itu, terkesan “merendahkan” Jokowi.
Sekali lagi tidak ada yang salah. Mungkin kurang tepat waktu dan tempatnya. Apalagi disiarkan terbuka. Kembali lagi, ungkapan Bu Mega dijadikan amunisi untuk menambah olok-olok kepada Jokowi yang notabene masih Presiden RI.
Ketika itu, Presiden tetap tersenyum tetapi sekejap berhenti. Apa artinya? Penulis yakin, tidak berkenan. Demi untuk menjaga adab saja, Jokowi tersenyum.
Satu dua tiga kali diulang, maka Presiden pasti berpikir dan merenung. Bagaimana keluar dari bayang-bayang sebagai petugas untuk menjadi diri sendiri. Hanya ada satu kata. Melawan! Kehormatan harus dijaga, dan dipertaruhkan.
Mungkin orang akan menggugat tentang tentang balas budi. Lho bukankah balas budi sudah dilakukan dengan memberi begitu banyak jabatan pada Bu Mega, juga menteri-menteri. Termasuk berbagai jabatan kepada orang-orang partai.
Lagi pula, benarkah dalam kosakata politik perlu rasa malu, atau pun balas budi? Tergantung situasi bukan?
Dengan tekanan demikian, maka kata “sabar” yang sering diungkapkan Pak Jokowi jadi tidak bermakna tunggal. Sabar menghadapi olok-olok Bu Mega. Sabar menunggu langkah politiknya. Sabar menghadapi realitas Gibran dicalonkan Golkar, dll.
Interpretasi ini bisa saja salah seperti saya uraikan sebelumnya, tetapi bisa saja benar. Sejarah yang akan membuktikan. Wallahu alam bisawab.***




 -------
-------