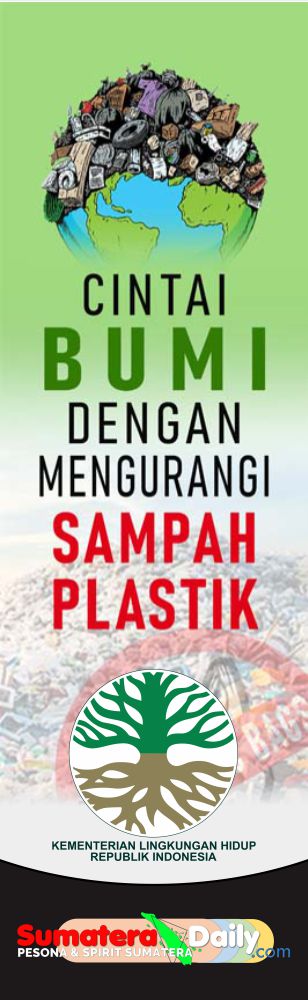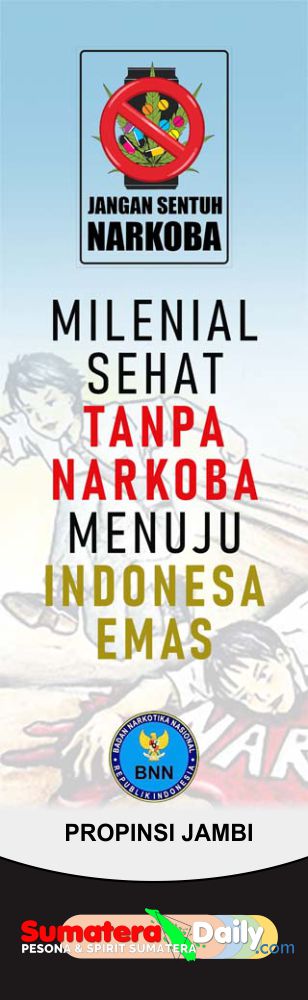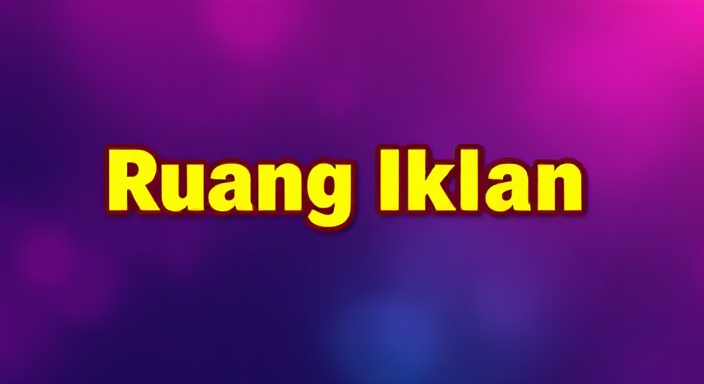Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP , Akademisi UIN STS Jambi
Dalam wacana pembangunan, kemiskinan kerap direduksi menjadi persoalan angka diukur melalui indikator konsumsi, kepemilikan aset fisik, dan akses terhadap infrastruktur dasar seperti rumah dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Pendekatan semacam ini memang menawarkan kemudahan dalam pengukuran dan perbandingan statistik, namun sering kali mengabaikan kompleksitas sosial, kultural, dan geografis yang menyertai realitas kemiskinan itu sendiri.
Misalnya, penduduk di wilayah pesisir dan rawa gambut yang tidak memiliki MCK permanen kerap langsung dikategorikan sebagai penduduk miskin, meskipun mereka telah lama beradaptasi dengan sistem sanitasi berbasis kearifan lokal yang fungsional.
Ketika kemiskinan dinilai hanya dari keberadaan jamban atau kondisi fisik rumah, maka pertanyaan yang lebih substansial pun terabaikan: Apakah seseorang benar-benar memiliki ruang dan kapasitas untuk menentukan arah hidupnya mengakses pendidikan yang berkualitas, mendapatkan pekerjaan yang layak, menikmati layanan kesehatan yang manusiawi, serta terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan publik tanpa harus terus-menerus tersandera oleh kemiskinan struktural yang diwariskan secara turun-temurun? Dalam konteks inilah, keandalan indikator perlu dikaji ulang agar tidak menjadi instrumen yang justru mengaburkan fakta sosial yang hendak diungkap.
Selama ini, pendekatan dalam mengukur kemiskinan masih terlalu terpaku pada indikator-indikator konvensional yang bersifat fisik dan statistik semata.
Ukuran seperti garis kemiskinan berdasarkan konsumsi, standar rumah layak huni, atau kepemilikan fasilitas dasar, seringkali dijadikan acuan tunggal tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial, geografis, dan perubahan zaman.
Akibatnya, realitas kemiskinan yang lebih luas yang mencakup keterasingan dari akses, kesempatan dan partisipasi kerap luput dari perhatian.
Ironisnya, di tengah dinamika sosial dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, instrumen pengukur kemiskinan kita masih terjebak pada cara pandang lama yang statis dan nyaris tak berubah.
Pendekatan lama dalam mengenali kemiskinan diukur secara kasat mata melalui rumah yang sederhana, pola konsumsi yang terbatas, atau keterbatasan fisik dalam memenuhi kebutuhan dasar masih sering dijadikan acuan hingga kini.
Namun, di era digital saat ini, indikator semacam itu tak lagi cukup. Seseorang bisa saja hidup dengan gaya hidup sederhana, bahkan tampak “biasa saja” dari luar, namun memiliki aset besar dalam bentuk investasi digital seperti saham, bitcoin, reksa dana, atau aset kripto lainnya.
Menurut Kementerian Perdagangan RI, jumlah investor kripto di Indonesia per Mei 2023 telah mencapai lebih dari 17 juta orang. Tidak sedikit dari mereka yang tinggal di pedesaan, mengenakan pakaian biasa, dan tidak menampakkan kemapanan secara fisik (Kominfo, 2023).
Ketika indikator sosial gagal menangkap realitas yang dinamis, maka bukan hanya pengukuran kemiskinan yang bermasalah, tetapi juga distribusi kebijakan yang menjadi bias dan rawan disalahgunakan.
Di sisi lain, muncul ironi baru dalam distribusi bantuan sosial. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), ternyata terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang tahun 2024 (Antara, 3 Juli 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa data administratif dan indikator bansos belum tentu mencerminkan realitas sosial-ekonomi yang akurat.
Ada warga yang secara data dinilai miskin dan berhak menerima bantuan, namun justru memiliki pengeluaran untuk hal-hal yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan dasar.
Sementara itu, ada pula warga yang tampak tidak miskin secara visual, tetapi sejatinya terjebak dalam kemiskinan struktural. Mereka tak memiliki akses pada pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang layak, atau bahkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
Ini adalah dimensi kemiskinan yang kerap luput dari radar statistik karena tidak tercermin dalam indikator material semata.
Kekeliruan serupa juga terjadi saat indikator fisik seperti kepemilikan MCK (mandi, cuci, kakus) dijadikan tolok ukur nasional tanpa memperhatikan konteks geografis. Di wilayah pesisir atau rawa gambut, standar MCK yang berlaku di daerah dataran tinggi tentu tidak relevan.
Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat sekitar 18 persen penduduk di wilayah pesisir dan rawa dikategorikan miskin karena tidak memiliki MCK permanen. Padahal masyarakat setempat telah lama beradaptasi dengan sistem sanitasi berbasis kearifan lokal yang fungsional dan sesuai dengan karakter lingkungan.
Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, pernah menyatakan bahwa kemiskinan sejatinya adalah ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai (poverty is the inability to live a life one has reason to value) (Sen, 1999). Artinya, kemiskinan tidak bisa sekadar dilihat dari sisi konsumsi atau kondisi fisik.
Ia juga harus dilihat dari keterbatasan pilihan hidup, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan untuk bermartabat di tengah masyarakat.
Dalam konteks ini, pendekatan multidimensi seperti yang ditawarkan oleh Human Development Index (HDI) dan Multidimensional Poverty Index (MPI) menjadi semakin relevan.
Indeks-indeks ini tidak hanya mengukur pendapatan, tetapi juga melihat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara menyeluruh.
Data dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) menunjukkan bahwa negara-negara yang menggunakan pendekatan multidimensi cenderung lebih akurat dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan (UNDP & OPHI, 2023).
Kemiskinan adalah isu yang kompleks, menyentuh aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural.
Penanganannya membutuhkan pendekatan lintas sektor yang menyeluruh tidak hanya berbasis bantuan, tetapi juga pemberdayaan, perbaikan tata kelola, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Mengatasi kemiskinan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Namun, kompleksitas itu kerap disederhanakan dalam praktik, sehingga pendekatan yang digunakan justru gagal menangkap esensi dari kemiskinan itu sendiri.
Karena itu, jika upaya pengentasan kemiskinan tidak sekadar menjadi jargon, maka cara pandang kita pun harus ikut berbenah. Tidak cukup hanya bertanya: “Apakah orang ini punya rumah dan MCK?”, tetapi juga: “Apakah dia bisa bermimpi dan mewujudkan hidup yang ia inginkan?” Tanpa pembaruan indikator yang mencerminkan dinamika zaman dan keberagaman wilayah, kita hanya akan terus terjebak mengejar bayang-bayang kemiskinan yang tampak di permukaan, namun kerap menyesatkan dalam kenyataannya.***